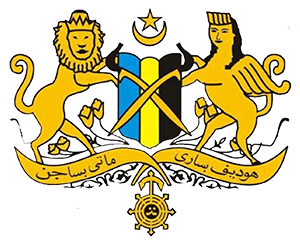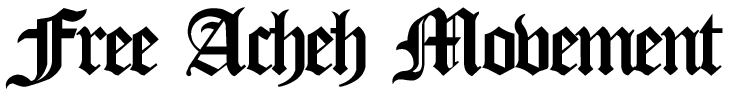Pahami Sejarah Acheh yang Benar Agar Kita Tidak Dibodoh-Bodohkan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab.
Pada 26 Maret 1873 Belanda memproklamirkan perang dengan Kerajaan Aceh. Sejak itulah tanah Aceh setapak demi setapak diduduki Belanda, hingga pusat istana pemerintahan Kerajaan Aceh (Dalam) dikuasai Belanda pada 24 Januari 1874. Kejatuhan Dalam itu diyakini akibat pengkhianatan dari dalam.
Belanda mengira dengan dikuasainya istana Sultan Aceh, Kerajaan Aceh sudah ditaklukkan, bahkan Belanda mengganti nama Bandar Aceh Darussalam ibu kota kerajaan Aceh menjadi Kutaraja.
Istana Sultan Aceh memang sengaja dikosongkan, karena saat itu seiring dengan kedatangan Belanda ke Aceh wabah kolera mencuat. Bahkan ratusan tentara dan orang hukuman Belanda yang dibawa ke Aceh sebagai pekerja paksa meninggal sebelum mendarat di Aceh karena wabah kolera.
Pada 28 Januari 1874 raja Aceh Sultan Alaidin Mahmud Syah mangkat di Lueng Bata dan dimakamkan di Pagar Aye. Beberapa hari kemudian jasadnya dipindahkan ke Cot Bada, Samahani, Aceh Besar karena khawatir makamnya akan dibongkar oleh Belanda.
Sultan Alaidin Mahmud Syah hanya memerintah Kerajaan Aceh selama empat tahun, yakni dari tahun 1870 hingga 1874. Ia menggantikan raja Aceh sebelumnya Sultan Alaidin Ibrahim Syah yang meninggal pada tahun 1870.
Tapi, meski hanya memimpin Kerajaan Aceh selama empat tahun saja, Sultan Alaidin Mahmud Syah sebelum meninggal sudah membentuk Kabinet Perang Kerajaan Aceh untuk menghadapi penjajah Belanda.
Kabinet Perang yang dibentuk Sultan Alaidin Mahmud Syah itu dipimpin oleh Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Kerajaan Aceh sekaligus sebagai Menteri Peperangan (Wazirul Harb).
Pengukuhan dan pelantikan Kabinet Perang Kerajaan Aceh dilakukan dalam Balairung Darud Donya. Pengangkatan itu disaksikan oleh tiga imam besar dan panglima tiga sagi pada 10 Zulkaidah 1288 Hijriah (1872 Masehi) di dalam Mesjid Baiturrahim Darud Donya. Dalam musyawarah itu hadir para ulama besar, menteri dan uleebalang seluruh Aceh.
Melalui Kabinet Perang Sulthan Alaiddin Mahmud Syah memutuskan akan melakukan perang total kalau Belanda menyerang Aceh. Sebagai tanda kesepakatan tekat tersebut, mereka yang mengikuti rapat kerajaan itu mengucapkan sumpah. Sumpah itu dipimpin oleh seorang ulama besar, Kadli Mu’adhham Mufti Besar Kerajaan Aceh, Syekh Marhaban bin Haji Muhammad Saleh Lambhuk dan disaksikan oleh para alim ulama.
Ketika Sultan Alaidin Mahmud Syah mangkat, diangkatlah anaknya Muhammad Daud Syah sebagai raja Aceh pada tahun 1874 ketika itu usianya baru tiga tahun. Penobatannya sebagai raja Aceh dilakukan di Masjid Indrapuri, Aceh Besar.
Karena Sultan Muhammad Daud Syah masih sangat muda dan belum punya kemampuan memimpin Kerajaan Aceh, maka para petinggi Kerajaan Aceh bersama para ulama melakukan musyawarah Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh. Majelis ini terdiri dari Tuwanku Muhammad Raja Keumala, Tuwanku Hasyim Banta Muda, Teuku Panglima Polem Raja Kuala dan Teungku Chik Di Tanoh Abee Syech Abdul Wahab. Musyawarah Tuha Peut Kerajaan Aceh itu memutuskan menarik semua kekuasaan raja ke hadapan Tuha Peut Kerajaan Aceh.
Nah, sejak saat itulah raja Aceh yang masih berusia 3 tahun itu hanya dijadikan sebagai simbul semata, sementara urusan pemerintahan dilakukan oleh para menteri bersama Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh. Jadi meski dalam perjalanan selanjutnya raja Aceh ditawan saat menjemput istrinya yang ditawan Belanda, ia menolak menandatangani penyerahan kekuasaan Kerajaan Aceh kepada Belanda, karena kekuasaannya sejak tahun 1874 sudah diserahkan kepada Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh. Jadi penawanan dia oleh Belanda bersifat pribadi. Karena tidak memperolah pengakuan kedaulatan itulah maka Belanda mengasingkan Sultan Muhammad Daud Syah ke Ambon.
Lalu siapa yang menjalankan pemerintahan Kerajaan Aceh dalam situasi perang? Dari sinilah muncul nama Teungku Chik Di Tiro ulama besar yang mampu mempersatukan rakyat Aceh untuk melawan Belanda.
Kembali lagi ke tahun 1874, setelah kekuasaan Sultan Muhammad Daod Syah itu ditarik oleh Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh, karena sultan saat itu masih berusia tiga tahun dan belum mampu memerintah kerajaan, apa lagi dalam suasana perang melawan penjajah Belanda, Majelis Tuha Peuet Kerajaan Aceh kembali melakukan musyawarah membahas kelanjutan pemerintahan.
Dalam musyawarah pada 28 Januari 1874 itu, Ketua Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh Tuanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan untuk mempersatukan rakyat Aceh di bawah satu komando dalam perang melawan penjajah Belanda, dibentuklah Wali Neugara.
Sebagai Wali Neugara pertama diangkat Teungku Chik Di Tiro dengan gelar Al Malik Al Mukarram Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman Bin Abdullah. Wali Neugara inilah yang mempersatukan rakyat Aceh dalam perang melawan penjajah Belanda.
Setelah diangkat menjadi Wali Neugara, Teungku Chik Di Tiro bersama ribuan pejuang Aceh berkali-kali melakukan penyerangan ke bivak-bivak dan benteng pertahanan Belanda. Pasukan Belanda kalang kabut menghadapi pejuang Aceh. pemerintah Kolonial Belanda tidak pernah aman berada di Aceh. Sejak saat itu Teungku Chik Di Tiro menjadi orang yang paling dicari oleh Pemerintah Kolonial Belanda.
Gubernur Sipil dan Militer Belanda kedua di Aceh Jenderal Laging Tobias yang menjabat dari tahun 1882 hingga 1884 mengakui Teungku Chik Di Tiro dan pasukannya merupakan pasukan tanggung dengan taktik gerilya yang sangat menyulitkan Belanda. Ia mengirim surat permintaan perdamaian kepada Teungku Chik Di Tiro, tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Teungku Chik Di Tiro. Perang terus berkecamuk.
Gagal mengajak Teungku Chik Di Tiro berdamai, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengambil kebijakan “Lini Konsentrasi”, tentara Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp dan benteng-benteng terpusat untuk menghindari perang.
Kebijakan lini konsentrasi ini diberlakukan pada masa Gubernur Sipil dan Militer Belanda di Aceh dijabat oleh Mayor Jenderal Demmeni. Ia dilantik menjadi gubernur pada September 1884 dan meninggal pada 13 Desember 1888.
Lini konsentrasi diciptakan oleh Mayor Jenderal AWP Weizel. Ia membuat serangkaian benteng di wilayah Aceh Besar yang dihubungkan dengan lori. Namun sistem ini tidak dapat memaksa pasukan pejuang Aceh untuk menyerah, bahkan sebaliknya terus menyerang.
Akibatnya, Belanda kehabisan banyak anggaran hanya untuk membangun benteng-benteng sebagai tempat konsentrasi pasukan. Selain itu, moral pasukan Belanda yang dikurung dalam benteng merosot, mencekam dalam suasana tegang dalam benteng. Kunjung mengunjung antar benteng di antara para istri opsir dan perwira Belanda harus dilakukan dengan menggunakan lori dengan pengawalan pasukan khusus.
Dana yang dihabiskan untuk membangun benteng lini konsentrasi dan rel lori penghubung antar benteng juga tidak sedikit. Belanda juga harus membentuk brigade sepeda lori yang mondar-mandir antar benteng. Belanda benar-benar tak dapat mengendalikan suasana di Aceh.
Sikap defensif pasukan Belanda itu kemudian diolok-olok oleh pejuang Aceh dengan mengirim surat-surat ancaman dan ajakan berperang di tempat terbuka, karena itu mental pasukan Belanda bertambah jatuh, mereka tidak berani menjawab ajakan perang dari pejuang Aceh. Dan sampai Belanda keluar dari Aceh pada tahun 1942, setelah 69 tahun berperang, Belanda tidak memperoleh pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Aceh.
Maka sebab itulah pada hari ini kita menyeru kepada semua pihak agar menghormati dan memahami sejarah Atjeh yang sebenar benarnya. Walaupun Negara Kesultanan Acheh masih dalam jajahan kolonialis hindunesia jawa tetapi Acheh tetap selalu ada pemiliknya. Ada pemilik yang masih bertanggung jawab dalam hak ketentuan sejarah. Jangan ada pihak pihak mana pun sama ada dari Acheh atau pun dari luar Acheh yang tanpa berfikir panjang mencampuri urusan penyelesaian politek Acheh secara sepihak. Harus diingatkan bahwa Acheh bukanlah harta ghanimah yang boleh diperebutkan. Acheh masih ada pihak2 yang berhak dan bertanggungjawab menjaga dan merawatnya. Anak cucu keturunan leluhur dari Sulthan Ali Mughayat Syah dan Sulthan Iskandar Muda meukuta alam serta dari keluarga turun temurun Wali Neugara Tengku Tjhik di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah masih ada dan masih berhak dan bertanggung jawab. Begitulah pelita penerang jalan dan drama sejarah Acheh yang sudah berlaku ratusan tahun yang lalu yang sudah menjadi ketentuannya dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas tanah pusaka mulia ini.
Kita juga tidak boleh melupakan satu lagi bagian yang sangat penting dalam ketatanegaraan kesultanan kerajaan Atjeh iaitu Institusi Ulama. Sewaktu Acheh di puncak keagungannya nama nama besar seperti Mufti Besar Keuradjeuen Atjeh Syeikh Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Besar Keuradjeuen Atjeh Syeikh Abdurraof Al Singkili, Kadhi Mu’adhham Mufti Besar Keuradjeuen Aceh Syekh Marhaban bin Haji Muhammad Saleh Lambhuk, Teungku Chik Di Tanoh Abee Syech Abdul Wahab dll selalu ada memainkan peran dan tanggung jawab dalam menata dan mengelola sebuah entiti politik kesultanan kerajaan Acheh Darussalam. Ini melambangkan bahwa Ulama’ dan Umara’ serta seluruh bangsa saling bahu membahu dan bekerjasama untuk kemakmuran dan kegemilangan Kesultanan Kerajaan Acheh Darussalam.
Hudep Beu-Sare, Mate Beu-Sadjan
Sikrek Gaphan, Saboh Kereunda.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Tengku Sulaiman Abdul Razak Tiro
Jubir Majlis Gerakan Atjeh Meurdehka Pusat
Stockholm, Sweden.
16 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H